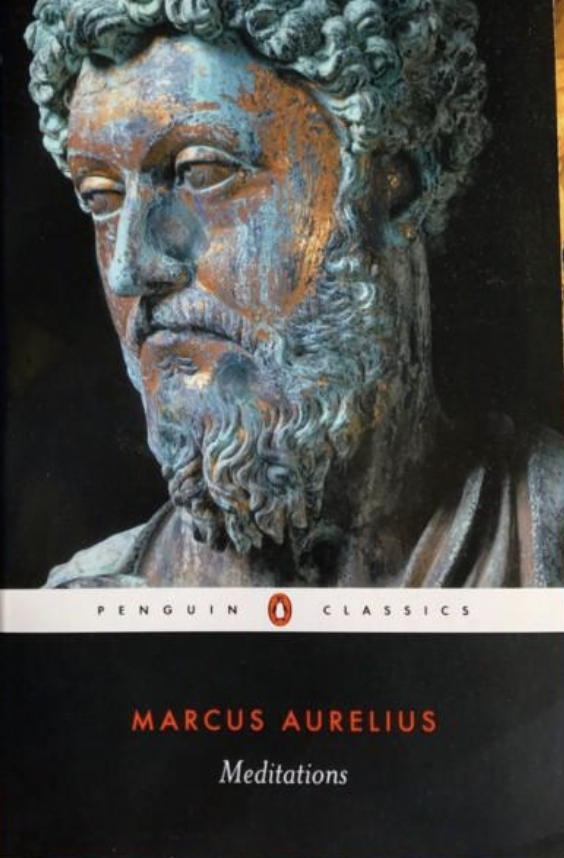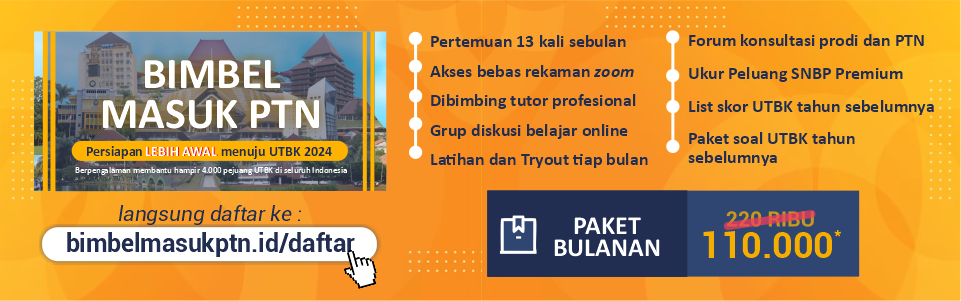Pada musim semi pertama tahun 180 M, Marcus Aurelius terbaring lemah di ranjangnya dalam keheningan yang dingin dan mencekam. Malam itu, ia mengalami sakit parah dan tahu betul bahwa dirinya sedang sekarat—tanpa harus diberitahu para tabibnya. Ia memberi isyarat kepada seorang perwira muda untuk mendekat dan lalu membisikkan sesuatu ke telinganya dengan suara serak. Selepasnya, Marcus kembali berbaring dengan begitu lemas, menutupi dahinya dengan selembar kain dan tertidur; meninggal dalam perasaan yang tenang pada malam ketujuh penyakitnya.
Di pagi hari, beberapa tabibnya mengumumkan kematian sang Kaisar, dan sontak kamp tersebut menjadi kacau-balau. Para prajurit dan penduduk dengan cepat memadati hampir seluruh jalanan Roma sembari menangis karena turut merasa terluka. Menurut Herodian, seorang sejarawan terkemuka kala itu, seluruh penjuru Kekaisaran berteriak histeris seolah-olah berada dalam satu paduan suara yang sama ketika berita kematian Marcus tersebar. Ketika keriuhan di luar semakin keras, para penjaga yang gemetaran bertanya kepada seorang perwira muda yang sebelumnya mendapat bisikan dari Marcus. Perwira itu sepertinya hendak berbicara tetapi kemudian berhenti sejenak. Sembari mengerutkan alisnya dengan penuh kegugupan, ia menyampaikan pesan terakhir Marcus: Pergilah ke matahari terbit, bisiknya, karena aku sudah terbenam.
Marcus Aurelius adalah satu di antara sekelumit tokoh klasik yang masih dapat berbicara banyak kepada kita hari ini. Melalui magnum opus-nya Meditations, kita dapat mengamati bagaimana ia menguraikan filsafat Stoicism dengan gaya bahasa yang sederhana, namun sekaligus begitu megah. Kesederhanaan bahasa itulah yang membuat karyanya mampu menjangkau pembaca secara luas, dan bahkan dijadikan sebagai petunjuk laku hidup oleh sebagian besar pembacanya. Dalam bab kedua On Liberty, John Stuart Mill menggambarkan Marcus sebagai “yang terbaik dan paling tercerahkan di antara orang-orang sezamannya”. Mill juga menilai Meditations sebagai “produk etika tertinggi dari pikiran klasik”.
Meditations merupakan buah perenungan Marcus yang rutin dilakukannya setiap malam di tenda-tenda perang dan ditulis dalam bahasa Yunani alih-alih bahasa Latin. Yunani adalah bahasa di mana filsafat diajarkan dan kiranya itu lebih disukai Marcus untuk tujuan menarik diri, bermeditasi, dan menjernihkan pikirannya. Kita juga dapat menduga bahwa bahasa Yunani dipilih sebagai sarana untuk mengasingkan diri dari retorika bahasa Latin yang saat itu dominan di Kekaisaran Romawi.
Manuskrip dan edisi cetak Meditations yang kita miliki hari ini sering ditampilkan dalam dua belas buku dan dibagi menjadi 488 entri—sebagian berisi wejangan panjang, tetapi beberapa di antaranya hanya kalimat tunggal. Buku pertama Meditations, tidak seperti sebelas buku berikutnya, berisi pernyataan-pernyataan wasiat terakhir sang Kaisar dan rasa terima kasihnya kepada mereka yang telah membimbing, memengaruhi, dan menginspirasi jalan hidupnya. Dari situ pula kita dapat mengetahui sebuah fakta menarik bahwa perjumpaan Marcus dengan filsafat bukanlah melalui guru pendidikannya, melainkan lewat guru lukisnya, Diognetus (1.6).
Serangkaian panjang nasihat dan refleksi Marcus dalam Meditations tampaknya tidak ditujukan untuk siapa pun selain dirinya sendiri, karena kata-katanya begitu pribadi dan diarahkan “ke dalam” sehingga sulit untuk mengetahui kepada siapa ia menulis. Meditations bukanlah sekadar transkrip entri dari jurnal harian Marcus. Sebagaimana kehidupan pribadinya, entri-entri ini menunjukkan tanda-tanda komposisi yang cermat karena disunting sebagai perenungannya. Ini adalah kesaksian Marcus terhadap berbagai keruwetan di zamannya dan bagaimana ia sendiri harus bertarung melawan hiruk-pikuk kehidupan, baik sebagai Kaisar maupun filsuf.
Berkat muatannya yang universal itulah, Meditations terasa sangat relevan untuk semua musim, khususnya di zaman kita yang setiap detiknya hampir selalu dipenuhi kebisingan tanpa makna. Para filsuf kontemporer menyebut situasi hari ini sebagai era post-truth; sebuah istilah aneh untuk menggambarkan terjadinya kekaburan hal-hal yang benar secara universal, dan orang-orang lebih percaya pada sesuatu yang memikat emosi daripada fakta objektif. Pada 2016 akhir, istilah post-truth menjadi Word of the Year dari Oxford Dictionary, yang menandakan adanya kesadaran massal tentang kepongahan peradaban kita, tetapi sekaligus menunjukkan ketidakpedulian yang luar biasa karena bagaimanapun juga, fenomena post-truth terus terjadi. Inilah Era Kebisingan, yang mana kebisingan tersebut dilakukan seraya dikutuk secara menyeluruh.
Era Kebisingan yang dimaksudkan sebenarnya bukanlah fenomena baru dalam sejarah manusia. Jauh sebelum sekarang, tepatnya di masa Yunani Klasik hingga keruntuhan Imperium Romawi, sudut-sudut kota terkemuka Eropa Barat sudah dibisingkan oleh pertarungan retorika yang berbelit-belit di antara para pria. Kebenaran dianggap sebagai sesuatu yang subjektif; jadi barang siapa yang memenangkan perdebatan, maka dialah yang benar. Kebisingan tersebut disokong secara masif oleh kaum Sofis, termasuk ketika Marcus Aurelius hidup. Marcus sendiri mengaku sangat benci dengan kebudayaan semacam itu, sebab baginya, kebenaran sejati berasal dari kekuatan rasio dan bukannya ditentukan oleh siapa yang menang debat (3.12).
Namun, perlu diakui bahwa berkat kebudayaan retorika itulah, Marcus menjadi banyak merenung dan semakin dekat dengan apa yang disebutnya “kodrat Alam”. Di tengah-tengah kebisingan yang tiada henti, Marcus membuktikan kekuatannya dalam menghadapi rupa-rupa keriuhan dan tetap bersahaja tanpa terbawa arus yang menyesatkan. Marcus menulis (2.7):
Apakah orang-orang dan lingkungan sekitar mengusikmu? Berhentilah dipusingkan oleh hal-hal di luar dirimu. Jangan mengkhawatirkan apa yang orang lain pikirkan tentangmu. Pikirkan saja apa yang kau kehendaki. Perhatikan gerakan pikiranmu dan fokuskan ia pada sesuatu yang berharga.
Petuah tersebut tentunya sangat relevan dengan apa yang kita hadapi hari ini, mulai dari kebisingan di sekitar kita tentang kekacauan ekonomi hingga keributan di media sosial tentang absurditas politik. Bahkan bersamaan dengan itu, kita masih dirisaukan oleh perang Rusia-Ukraina yang seiring waktu semakin berdampak pada keseharian kita—misalnya kenaikan harga minyak dunia yang berimbas pada kelangkaan bahan bakar. Berita-berita yang kita dengar tampaknya hanya seputar aneka krisis yang sedang terjadi, dan itu cukup untuk memekakkan telinga kita. Dengan begitu, kita bukan hanya dibombardir secara empiris, tetapi juga secara mental.
Kewarasan kita terus dipertaruhkan dengan rentetan kebisingan yang kadang-kadang membuat kita terlena, tetapi kerap kali sangat mengganggu. Perkembangan zaman tampaknya tidak mengarahkan kita ke dimensi yang lebih baik; malahan berbagai produk baru dari teknologi menjadikan bangsa kita—yang tadinya memang tidak berwatak ulet—semakin manja dan memilih untuk apatis terhadap beragam persoalan publik. Ketidakpedulian tersebut, pada akhirnya, menyimpang dari nilai-nilai demokrasi, sebab beberapa keputusan politik yang bersifat vital tidak lagi ditentukan oleh partisipasi, melainkan lewat mobilisasi.
Kemanjaan yang dipicu oleh kemudahan zaman membuat manusia Indonesia mengalami alienasi yang begitu mengakar dan tidak lagi mudah untuk diatasi. Kini—ketika Indonesia disebut-sebut akan mengalami bonus demografi—generasi muda kita nyaris kehilangan segala idealismenya, baik perihal kehidupan berbangsa maupun dimensi pribadi, seolah telah menjadi “anak zamannya” yang terseret arus begitu saja dan tidak mampu mengendalikan diri sendiri.
Pada titik inilah, Meditations dapat menjadi obat filosofis bagi kita semua tentang bagaimana kiat mempertahankan kewarasan di tengah-tengah kebisingan yang beriringan dengan kebohongan. Sebagaimana Marcus sendiri juga mengalami fenomena serupa, ia menulis (4.32):
Fokuslah pada apa yang penting. Berikan segenap perhatian pada hal-hal besar, dan kurangi perhatian pada hal-hal kecil.
Dengan demikian, cara Marcus dalam menghadapi ketidakjelasan gempuran narasi adalah dengan menambah pengetahuannya tentang sesuatu yang menarik dan penting baginya, tetapi sekaligus membuang segenap hal yang kiranya tidak perlu dipedulikan oleh pikirannya. Strategi ini dapat diibaratkan seperti membereskan kamar: kita menata dengan rapi benda-benda yang dibutuhkan, seraya membuang sampah-sampah yang selama ini berserakan. Menurut Marcus, hidup adalah sebuah ziarah dan perjuangan, sebab waktu yang kita miliki teramat singkat (2.17). Jadi apabila kita disibukkan oleh persoalan-persoalan sepele dan hal-hal kecil, kita telah menyia-nyiakan hidup kita.
Melalui berbagai saluran komunikasi, sebenarnya kita masih menemukan argumen-argumen logis yang bertebaran, tetapi kebanyakan adalah hasil dari rasionalisasi yang dibungkus dengan lagak cendekia, padahal jiwa kritis itu sendiri hanyalah suatu topeng dari kesinisan yang sudah terlanjur melekat dalam diri. Akibatnya, rupa-rupa hegemoni semakin luput untuk disadari, dan bahkan para pencetus memperlakukan manusia secara mekanistik, tidak berbeda seperti “mesin berkesadaran” yang bisa dikendalikan melalui “remot” khusus: kontrol atas sumber daya, propaganda, adu domba. Dehumanisasi ada di mana-mana, tetapi yang tertindas masih saja sibuk memeriksa layar beranda mereka dan pergi ke klub-klub malam tanpa pernah tahu ada yang menggerogotinya perlahan-lahan dari dalam.
Masifnya gerakan disrupsi secara global membuat orang-orang terus mencari kesejatiannya di luar diri mereka sendiri, terutama via media sosial. Kini kita tidak lagi melihat kolaborasi yang membentuk keharmonisan tatanan dunia, melainkan hampir semua hal berbasis pada kompetisi, sebagaimana adagium Thomas Hobbes: homo homini lupus. Kecemasan ada di mana-mana dan terus meneror kita karena begitu takut bahwa kita tidak akan mampu bersaing dengan yang lain, kemudian terlempar ke dalam keterasingan yang sedemikian pedih. Tetapi, menurut Marcus, tekanan semacam itu bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti, sebab hidup itu sendiri hanyalah sebuah perjalanan (3.3).
Kau memulainya; kau berlayar; dan, ketika kau mencapai pantai yang jauh, kau keluar dari perahu.
Hasrat untuk mencapai ketenaran juga merupakan sesuatu yang konyol bagi Marcus. Bagaimanapun juga, ketenaran adalah efek samping dari apa yang kita lakukan tanpa perlu dikehendaki, apalagi dikejar. Ketenaran harus terjadi dengan sendirinya sebagai hasil dari jerih payah dalam mengejar sesuatu yang lebih besar. Selayaknya Marcus sendiri, ia hanya melaksanakan tanggung jawabnya sebagai Kaisar Romawi, dan ketenaran itu datang secara otomatis dalam bentuk kekaguman dan ketakjuban orang-orang terhadapnya, termasuk di zaman kita. Marcus menulis (3.10):
Apakah kau mencari ketenaran, sehingga kau akan hidup dalam ingatan orang-orang setelah kau mati? Ingatlah bahwa hari-hari mereka juga singkat—mereka hampir tidak punya waktu untuk mengenal diri mereka sendiri. Dan bahkan jika mereka hidup sepuluh ribu tahun dan menyimpan kenangan tentangmu, apa gunanya bagimu? Hidup hanyalah untuk yang hidup.
Berjuang untuk ketenaran, bagi Marcus, dapat diibaratkan seperti mengumpulkan tumpukan pasir yang besar; keesokannya, angin datang dan meniup segalanya. Apa yang utama adalah hidup bersahaja; berpegang pada nilai-nilai keugaharian dan menjalani keseharian dengan sederhana. Hidup bersahaja bukan berarti bersikap pasrah kepada hidup atau—seperti yang sering dikatakan orang—mengalir seperti air. Tidak; hidup bersahaja adalah sikap mengiyakan kehidupan dengan penuh penyambutan, karena bukan hanya kedatangan yang baik akan disusul oleh yang buruk, tetapi keduanya memang tidak terpisahkan sebagaimana abu-abu yang mewakili hitam dan putih. Filsafat Stoicism menyebut sikap demikian dengan Amor Fati. Marcus memperingatkan dirinya sendiri (11.12):
Biarlah jiwamu tenteram dengan tidak mengejar—atau lari dari—apa pun.
Proposal utama lainnya dari Meditations adalah kepercayaan akan pentingnya untuk hidup di masa kini; bukan di masa lalu dan/atau di masa depan, tidak di seluruh keabadian. Hidup saat ini dan di sini bukan berarti sikap untuk melupakan masa lalu dan tidak memedulikan masa depan. Yang dimaksud Marcus adalah, kita tidak boleh terikat dan bergantung pada apa pun selain phusis (kodrat) manusia itu sendiri, misalnya perihal bernalar dan berpolitik (zoon politicon). Apa pun selain dari itu, maka seseorang telah menentang apa yang disebut Marcus sebagai “hukum Alam” (12.1).
Kau telah membayangkan betapa senangnya perasaanmu apabila suatu hari nanti, kau terus mengikuti jalan filsafat. Faktanya, keadaan terberkati yang kaucari sudah tersedia saat ini. Lepaskan saja masa lalu, percayakan masa depan pada takdir, dan pastikan saat ini kau telah selaras dengan Alam dan rasio.
Pada akhirnya, Meditations merupakan obat penawar hati yang akan selamanya relevan dengan semua musim. Penyampaian filsafatnya yang ringan sekaligus menawan membuat Meditations mampu menjangkau pembaca secara luas, terlepas dari apa pun budayanya. Proyek perihal hidup bersahaja yang termuat di dalamnya terbukti amatlah cocok dengan apa yang kita butuhkan hari ini, yaitu sebuah masa di mana kebisingan terus bergema tanpa henti untuk mencampuradukkan antara kebenaran dan kepalsuan. Memang, dikarenakan serat-serat Meditations adalah hasil dari permenungan-permenungan Marcus untuk zamannya, beberapa wejangan kiranya perlu dikontekstualisasikan lebih lanjut supaya lebih relevan bagi masing-masing pembaca. Tapi bagaimanapun juga, bacalah Meditations. Bagi saya, buku itu tak terlupakan.
Kontributor Media Edukasi Indonesia : Muhammad Andi Firmansyah